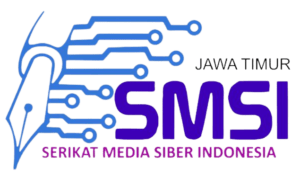Dari sudut pandang linguistik, konsumsi dapat di pandang sebagi proses mengunakan atau mendeskontruksi tanda-tanda yang terkandung di dalam obyek oleh para konsumer, dalam rangka memperoleh status sosial, perestise, dan simbol simbol tertentu bagi para pemakainya.
Di era modernisme sekarang, masyarakat membeli barang dan jasa bukan sekedar nilai manfaatnya atau karena terdesak kebutuhan, tapi karena pengaruh (hegemoni) sebuah gaya hidup konsumtif yang didorong “gengsi” agar tidak disebut ketinggalan jaman atau sebagai tanda dari status sosial seseorang. Mereka seakan malu bergaul-kumpul jika tak mengenakan “fashion” yang bermerek mahal. Istilah anak 2022 sekarang “fashion week”. Slebew, katanya.
Tak heran jika, dalam sebuah pergelaran industri busana misalnya, para penikmat berlomba-lomba mendatanginya. Mereka menyaksikan tren busana baru yang tak lain tujuanya adalah, untuk mengetahui (membeli juga jika cocok) apa yang sedang in dan apa yang sudah out dalam satu musim busana tertentu.
Gaya hidup masyarakat ini tidak lepas dari peranan kaum kapitalis yang memang sengaja menciptakan sistem ekonomi dengan tujuan menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tanpa memperhitungkan dampak buruknya terhadap kehidupan masyarakat.
Misalnya, dalam masyarakat industri, objek konsumsi yang berupa komoditi tidak lagi sekedar manfaat (nilai guna) dan harga (nilai tukar). Selebihnya, apa yang kita konsumsi kini melambangkan status, simbolis, prestise, dan kehormatan. Poinnya, objek dibeli hanya karena makna simbolik yang melekat di dalamnya, bukan karena harga (manfaatnya).
Pemuasan terhadap kebutuhan semu tersebut mungkin membahagiakan masing-masing individu. Namun menurut Marcuse, kebahagiaan itu juga adalah sesuatu yang semu dan tidak boleh dipertahankan karena, menghambat perkembangan kemampuan individu untuk mengenali kekurangan masyarakat secara holistik. Lebih dari itu, juga menghambat upaya untuk mengatasi kekurangan tersebut.
Dalam memenuhi kebutuhan semu, biasanya orang tidak mengetahui mengapa ia membutuhkannya. Dorongan untuk membeli dan menggunakannya tidak sungguh-sungguh timbul dari dalam dirinya sendiri, melainkan hanya sekedar melihat orang lain berbuat begitu. Kebutuhan itu datang dari luar, dan individu tidak mampu menguasai dirinya terhadap tekanan yang datang.
Syahdan, sistem kapitalis membuat kebudayaan menjadi suatu tawaran kebudayaan yang penuh kesenangan, fantasi dan menghibur serta mampu mengembangkan imajinasi tanpa batas. Bagi kaum kapitalis, dengan memproduksi budaya konsumtif dan hedonis pada masyarakat massa, (ia yakin dengan itu) akan mendongkrak hasil penjualan mereka dengan keuntungan sebanyak mungkin, sehingga mereka selalu merangsang tumbuhnya perilaku konsumen yang makin loyal dan adiktif. Wallahu a’lam bisshawaab.
)* Alumni PP Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo. Sekarang Nyantri di PP Nurul Jadid dan Kader PMII Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.