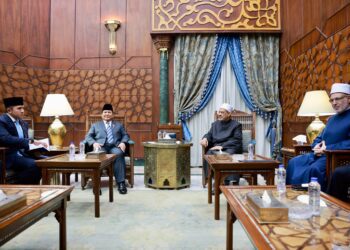Mutiara menguraikan, relasi pemerintah China cukup sensitif tetapi dalam perkembangannya, pemerintah mengembangkan berbagai aturan untuk pemerintah lokal termasuk di dalamnya kebebasan beragama.
“Nah, konteks ini memicu perkembangan kelompok sparatis Uighur yang dalam melakukan gerakan politiknya berjejaring dengan aktor-aktor eksternal dari Xinjiang termasuk gerakan teror yang meresahkan politik negara-negara tetangga, “jelas dosen muda itu.
Menyorot kasus Xinjiang, pengamat politik Internasional yang juga Direktur Sino-Nusantara Institute, Ahmad Syaifudin Zuhri, dalam makalahnya menyebut ada 47 negara anggota PBB diantaranya yang menyetujui dilakukannya debat terkait perilaku China terhadap muslim Uighur berjumlah 17 negara.
“Sedangkan yang menolak, pada dasarnya bukan negara Barat berjumlah 19 negara. Kemudian, 11 negara lainnya menyatakan abstain, “ujar kandidat Ph.D dari Central China Normal University yang juga pernah tinggal di China sejak 2011 hingga 2020 lalu.
Dalam materinya, Zuhri juga memetakan kemungkinan yang menjadi sumber konflik antara China dengan Amerika Serikat. Beberapa topik yang kemungkinan menjadi pemicunya antara lain terkait isu demokrasi dan teritori/ wilayah, persoalan perang dagang AS-China, problem keamanan di Laut China Selatan, hingga teknologi.
Sementara itu, Novi Basuki lebih berbicara pada persoalan akar konflik di Xinjiang. Penulis buku Islam di China itu menyebut isu Uighur serta campur tangan Barat di Xinjiang sering muncul di permukaan akibat adanya benturan komunisme dengan Islam Uighur.
Novi dalam pemaparannya berusaha membedah cikal bakal penduduk asli Xinjiang. Dikatakan, Inggris dan Rusia menyokong Ya’qub Beg untuk mendirikan negara di Xinjiang Selatan.
“Pendirian negara pada saat itu di era dinasti Qing pada kisaran 1865-1878. Saat dinasti Qing mulai melemah, “paparnya.
Novi yang juga pernah menyelesaikannya studi di Tiongkok menjelaskan secara detil terkait sosio-politik yang terjadi pada waktu itu. Sebagai penutup materinya, ia mengungkapkan bahwa Amerika berupaya untuk memainkan kartu pada isu Uighur di Xinjiang.
“China yang komunis saat ini sedang menguat, maka Amerika kemudian memainkan kartu Uighur untuk membendung powershift”, tutupnya.
Seminar yang dikonsep hybrid offline dan online itu diikuti 400 lebih peserta. Sesi diskusi menambah suasana makin meriah, terutama antusias peserta yang terdiri atas mahasiswa, akademisi hingga pemerhati masalah Xinjiang.