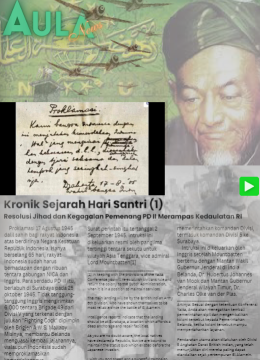Oleh: Salman Akif Faylasuf *
Salah satu intisari politik (al-siyasah) adalah pemimpin atau imamah. Secara umum, imamah di bagi dua, pertama imamah keagamaan, kedua imamah politik (yang sekaligus mencakup imamah keagamaan). Karena itu, penguasa atau pemimpin dalam Islam (Imam Negara) juga menjadi imam dalam shalat. Penyatuan antara imamah politik dengan imamah dalam shalat di Indonesia sudah buyar, berbeda dengan Arab Saudi, Turki dan Negara Islam lainnya yang masih kuat.
Pertanyaannya, bagaimana jika ada orang keliru berpendapat dalam masalah politik? Siapakah yang bertanggung jawab? Misalnya, jika ada orang Syi’ah berpendapat bahwa imamah hanya menjadi monopoli Ahlu Al-Bait, maka kita tidak boleh mengkafirkannya, karena kesalahan dalam imamah tidak dapat mengantarkan menjadi kafir (imamah tidak masuk bagian akidah atau ushul al-dhin disamping juga tidak menganggap bohong Nabi Saw). Pun dengan orang Syiah mengatakan bahwa yang berhak mengganti Nabi Saw adalah Sayyidina Ali.
Atau seperti pendapatnya al-A’sham, salah satu Tokoh Mu’tazilah mengatakan, “Imam tidak harus ada, masyarakat tidak membutuhkan pemimpin jika mereka bisa mengatur dirinya secara alamiah, dan Negara tidaklah menjadi sebuah keharusan”. Baginya, Negara terlalu mencampuri urusan internal sebagai komunitas yang bisa mengatur dirinya.
Syahdan, menurut al-Ghazali, baik ada yang mengatakan kepemimpinan bagian dari iman seperti pendapat kelompok Syi’ah, atau mengkafirkan kelompok Syi’ah seperti Salafi dan Wahabi, kita tidak perlu untuk meresponnya. Al-Ghazali juga menyatakan, posisi sebenarnya Sunni mayoritas, ia cenderung tidak mencari dan membuat masalah. Disebut Sunni, bukan berarti Mu’tazilah, Salafi, Wahabi dan lainnya tidak masuk kategori Sunni, melainkan semuanya bagian dari Sunni meskipun berbeda-beda.
Kita tahu, misalnya, Sunni ala NU mempunyai ciri pertama, mengikuti sistem bermazhab dalam beragama; kedua, mengikuti akidah Asy’ariyah dan Maturidiyah dalam bidang teologi; ketiga, mengikuti tasawufnya dalam ilmu akhlaq (kerohanian). Inilah Sunni mayoritas yang ada sejak abad-10 M hingga sekarang. Berbeda dengan Muhammadiyah yang merujuk langsung kepada al-Qur’an dan as-Sunnah.
Karena itu, menurut Gus Ulil, jika ada orang Sunni dengan mudah mengkafirkan satu kelompok, sudah pasti mereka bukan Sunni mayortitas, sebagaimana termaktub dalam kitab Faishal al-Tafriqah, bahwa Sunni mayoritas selalu menahan mulut untuk tidak mencampuri imannya orang lain. Tidak mengherankan, sambung Gus Ulil, jika sebagian muslim senang berteman dengan orang non-muslim, karena toleransi antara sesama muslim susah ketimbang toleransi kepada umat lain. Dan permusuhan golongan dalam Islam lebih keras dari permusuhan orang Kristen misalnya.